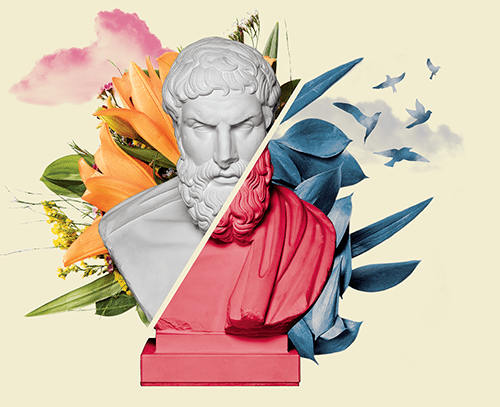Epicurus Gagalkan Bom Bunuh Diri
Gelembung air mata mengambang di pelupuk mata seorang perempuan usai menulis surat wasiat kepada orang tuanya. Namanya adalah Calianda (C), sarjana sains dari universitas ternama. Ia masih tak rela, tetapi keyakinan membuatnya bersedia. “Semoga pengorbananku di jalan suci ini dapat menyelamatkan kalian di akhirat kelak,” tutupnya dalam surat wasiat tersebut.
C kemudian bergegas pada Minggu pagi yang lembab. Niatnya telah matang dengan raut wajah seperti sedang menahan tangis. Semua perlengkapan sudah ia persiapkan sejak subuh. Ia mengambil rompi yang tergantung di pintu kamar kemudian mengisi satu-persatu bom pipa yang siap diledakan dengan tubuhnya.
C berencana meledakkan gereja yang sedang melaksankan Ibadah Minggu tak jauh dari rumahnya. Ia mendapatkan perintah bahwa gereja itu adalah bagian dari misinya sebagai sarana untuk medapatkan mati syahid dan peringatan bagi penguasa yang zalim.
Dalam perjalan yang sekira 200 meter dari rumahnya menuju gereja, C berpapasan dengan seorang lelaki tua urakan berumur 80-an sedang duduk memotong kuku dengan tenang dan bahagia di emperan toko yang tutup. Namanya Epicurus (E). C menatap E dengan gelisah dari jarak sepuluh meter sambil melangkah cepat. E pun menatap balik, namun dengan kesan ibah. E seperti melihat beban yang berkilo-kilo beratnya menggantung di mata C.
E: “Semoga harimu menyenangkan, nak. Nikmati dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan,” sapa E ketika C lewat tepat di hadapannya. Namun C terus berjalan. Ia menghindari terlibat komunikasi dengan orang-orang yang ia temui, bahkan jika itu teman dekatnya. Setelah C melewati E lima langkah, C tiba-tiba berhenti. Dadanya seperti diselimuti kabut penasaran. Siapa kakek itu, pikirnya. Jalannya melambat sebelum kemudian berbalik dan menyapa E.
C: “Maaf, kakek bilang apa tadi?” tanya C. Napasnya berdesakan. Ia merasa sedang di ambang kebingungan. “Apakah kakek tahu apa yang akan saya lakukan?”
E: “Duduklah di samping saya. Ceritakan apa yang membuat dirimu tampak begitu gunda. Nih, minum teh dingin ini. Saya tadi kebetulan membeli dua botol.”
C: “Terima kasih,” ujar C. Ia mengambil teh itu sambil duduk termenung membayangkan sifat seorang kakek di sebalahnya sedang memotong kuku.
E: “Kamu senang melakukan hal apa?”
C: “Saya senang memasak dan bernyanyi,” jawab C. “Tetapi itu membuat saya lupa pada hidup setelah mati, saya jadi lupa Tuhan. Ustaz saya bilang dunia itu tipu daya.”
E: “Oh, begitu,” kata E sambil meniup-niup kukunya yang selesai dipotong. “Jika saat ini kau tidak bisa memasak, atau dilarang memasak, apakah kau menjadi tidak senang?”
C: “Tentu. Saya bakal jadi marah-marah. Apa yang saya senangi kemudian dirampas atau diganggu itu menyakitkan,” C mulai merasa tenggelam dalam obrolan mereka. Kecurigaannya terhadap E mulai memudar.
E: “Sakitnya itu di mana?”
C: “Sakitnya tuh di sini.”
E: “Mengapa kamu bernyanyi?”
C: “Hahaha. Saya tidak sedang bernyanyi, kakek. Yang saya maksud di sini itu di hati, perasaan saya,” kata C, tertawa lepas. Ia mulai lupa kalau di dalam bajunya ada rompi berisi bahan peledak yang siap mencabik-cabik daging mereka berdua.
E: “Kesenangan itu ada dua. Yang satu kesenangan fisik dan yang kedua kesenangan mental. Kesenagan fisik antara lain makan, minum, dan lain-lain. Setelah terpenuhi kesenangan tersebut, maka selesai sudah urusan. Berbeda dengan kesenangan mental, kesenangan ini bertahan lama dan yang terbaik. Jadi kesenangan dan rasa sakit fisik hanya menyangkut saat ini, sedangkan mental bisa sangat panjang waktunya.”
C: “Kalau begitu, rasa sakit mental lebih berbahaya ketimbang rasa sakit fisik?” tanya C dengan saksama. Sekejap ia membuka botol tehnya yang tidak lagi dingin dan meminumnya dengan sekali tuang.
E: “Jelas. Rasa sakit pada mental adalah penghancur terbesar kesenangan atau kebahagiaan seseorang. Faktornya bisa karena masa lalu atau kecemasan pada masa depan.”
C: “Apakah itu juga termasuk takut masuk neraka setelah mati?” C mulai mengidentifikasi dirinya dengan apa yang dikatakan E–apakah tindakannya melakukan bom bunuh diri adalah suatu kesenangan fisik atau mental jika itu sudah dilakukan.
E: “Iya, itu termasuk. Ketakutan akan sesuatu di depan, termasuk setelah kematian.”
C: “Jika begitu, aku harus menolak percaya akan kehidupan setelah kematian?”
E: “Benar.”
C: “Ah, kakek kafir!” sergah C. Imannya terasa diganggu.
E: “Tunggu dulu. Saya tahu masalah kamu. Ini soal bagaimana mendapatkan hakikat kesenangan,” kata E sembari menenangkan C yang tampak gusar. “Begini, jika kesenangan adalah hasil dari apa yang kita inginkan, maka kita harus teliti membedakan beberapa keinginan. Coba saya tanya, apa keinginan terbesar kamu dalam hidup?”
C: “Saya ingin negara ini menganut sistem berdasarkan ajaran agama. Dan saya akan memperjuangkan itu meski nyawa saya melayang. Itu diwajibkan dalam agama saya.”
E: “Wah,” E tercengang mendengar jawaban C. Betapa ilusif dan sia-sianya keinginan ini, pikir E. “Kalau keinginan kamu itu terpenuhi, apakah lantas kamu senang? Itu pun kalau kamu tidak mati ditembak saat berjuang, tetapi kalau mati, kesenangan apalagi yang bisa kamu dapatkan?”
C: “Saya mendapatkan keselamatan di akhirat.”
E: “Ada tiga jenis keinginan: keinginan alami, alami tetapi tidak perlu dan yang sia-sia atau kosong. Untuk yang pertama, yaitu termasuk makan, tempat tinggal, dan sejenisnya. Keinginan ini mudah untuk dipuaskan dan tidak mungkin untuk ditiadakan. Alam sudah mengatur itu dan sifatnya terbatas. Jika seseorang lapar, ia hanya butuh makanan yang terbatas untuk mengenyangkan perutnya. Kedua, keinginan alami tetapi tidak perlu. Seseorang tidak perlu makan makanan mewah untuk bertahan hidup, meskipun makanan tersebut tersedia di hadapannya. Sebab, takutnya, ketergantungan atas jenis makanan tertentu dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. Jika kamu ingin membuat saudaramu kaya, jangan beri ia banyak uang, kurangi keinginannya. Ketiga, keinginan yang sia-sia. Keinginan ini termasuk keinginan akan kekuasaan tanpa batas, kekayaan, ketenaran, dan sejenisnya. Keinginan kamu untuk memperoleh surga setelah mati masuk kategori ini, apalagi untuk mencapai itu harus menghilangkan nyawa orang lain. Mengapa ini keinginan yang sia-sia? Sebab ia tidak terbatas—sulit dipuaskan karena tidak punya batasan alami.
C: “Kakek, mengapa anda seperti sedang memanipulasi iman saya? Anda tidak tahu bahwa saya sekarang sedang dalam perjalanan menegakkan agama saya? Bahwa dalam pakayan saya ada…” kata C memperingatkan E. Namun dadanya kini bimbang mendengarkan penjelasan E perihal kesenangan yang sia-sia. Jiwanya meronta namun diam-diam tampak terus berharap nasihat bijak E.
E: “Sejak bayi, keinginan kita sangat sederhana. Tetapi setelah dewasa, kita menjadi begitu rumit. Itu karena sebagian besar pikiran kita dibentuk oleh masyarakat. Keinginan kita saat menjadi manusia dewasa lebih banyak yang sia-sia ketimbang yang sedarhana dan diperlukan, akibatnya kita juga lebih banyak menderita.
C: “Bukankah kita menjadi lebih egois ketika berpikir hanya untuk kesenangan kita sendiri? Saya saat ini sedang memperjuangkan agama yang lebih mulia dari diri saya dan orang-orang di luar agama tersebut.
E: “Berarti kamu berani membunuh demi keyakinanmu itu?”
C: “Iya. Sebab agama saya suci, lebih utama, dan tertinggi dari semua yang ada di semesta.”
E: “Bukankah manusia juga ciptaan Tuhan sama seperti agama yang kamu yakini?”
C: “Memang begitu. Anda paham kan maksud saya?” C coba bertahan dengan argumennya, meski dia berpikir ada yang berlebihan. Ia merasa terlalu buta untuk agama yang dikatakannya suci.
E: “Kamu tidak adil,” kata E memperjelas maksud isi pikirannya.
C: “Loh, mengapa bisa begitu?” C membanting botol tehnya. Keyakinannya semakin tercerai-berai. Ia juga semakin yakin E sedang mengubahnya. “Coba anda jelaskan secara singkat. Aku curiga kakek bagian dari komunis-kafir-liberal.”
E: “Jika kamu sangat marah karena saya mengutarakan sesuatu yang bertentangan dengan iman kamu, maafkan saya. Saya tidak bersedia memberi makan apa yang ingin kamu makan. Namun begini, apa yang disebut keadilan adalah kesepakatan untuk tidak merugikan atau dirugikan. Kita pada dasarnya sudah memilih prakonsepsi tentang apa yang berguna dalam asosiasi timbal balik dalam hidup bersama. Artinya, dalam sebuah kemunitas, kita membuat kesepakatan untuk saling menjaga batas. Komunitas itu kemudian berfungsi menjaga hidup dari bahaya alam liar dan kecenderungan kejahatan manusia lain. Dengan demikian, apa yang disebut adil jika dan hanya jika ada kesepakatan seperti itu. Itulah mengapa saya menyebut kamu tidak adil jika begitu caramu memperjuangkan agamamu. Anda merugikan orang lain—melukai mereka bahkan membunuh mereka.”
C: “Ustaz saya tidak pernah membuat saya berpikir keras seperti ini, hanya kamu, kakek. Saya sadar, saya tidak pernah diajak berpikir,” ujar C dengan napas berat. Niatnya perlahan luruh. Ia ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada E, namun bayangan dosa masih melayang di atas kepalanya.
E: Demikianlah manusia jika berpikir. Ia bisa melihat kebanaran dan menjadi bijaksana. Kamu masih muda, gunakanlah waktumu untuk bersenang-senang tanpa harus merugikan orang lain. Kamu diajari untuk tidak puas pada hal-hal yang dianggap kecil oleh ustazmu, dan memberimu ilusi yang merusak. Orang yang tidak puas dengan yang sedikit, tidak akan pernah puas dengan apapun.”
C: “Saya sebenarnya ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Tetapi apakah aku harus percaya kepadamu kakek, yang liberal-kafir-komunis?” C perlahan membuka pakaian panjangnya yang menutupi rompi berisi bom pipa.
E: “Apapun nama yang kamu sematkan kepadaku, bukanlah soal. Saya hanya mengajakmu berpikir,” ujar E dengan lembut. “Tunggu, apa yang ada di balik bajumu?”
C: “Tidak ada apa-apa, kakek. Maaf saya harus pulang.” Sebelum bergegas, C terpaksa menunjukkan apa yang ada di balik bajunya. “Kakek menyelamatkan banyak orang di gereja. Dan terima kasih, kakek sudah membuatku tertawa. Saya jarang tertawa akhir-akhir ini.”
E: “Sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi,” kata E sembari melambaikan tangannya.